IBN TAIMIYAH DAN PEMIKIRAN POLITIKNYA
Oleh: A. Saifuddin
A. Pendahuluan
Ketika mendengar dan berbicara tentang sosok Ibn Taimiyah, maka terbersit di ingatan penulis komentar-komentar para kiyai dan ustadz ketika masih di pondok pesantren bahwa tokoh yang satu ini meskipun 'alim tapi karena banyak menghujat dan bahkan mengkafirkan para ulama, ia dianggap kafir, zindiq, dan term-term semacamnya.[1] Akibatnya tokoh ini tidak begitu dikenal (dimajhulkan) di kalangan pesantren yang begitu kuat memegangi tradisi ahl al-sunnah wa al-jama'ah. Tidak mengherankan pula jika penulis yang dibesarkan di kalangan pesantren baru sedikit mengetahui tokoh ini ketika sudah di bangku kuliah.
Namun, terlepas dari kontroversi sosok seorang Ibn Taimiyah, menurut penulis, tidak bijak jika kemudian melupakan dan tidak mau mempelajari pemikiran-pemikirannya, terutama yang berkaitan dengan politik—sebagai bidang yang menonjol ia bahas—karena sikap a-priori dan asumsi-asumsi yang kita bangun belum tentu sepenuhnya mengandung kebenaran. Sebaliknya, akibat yang ditimbulkan adalah sangat jelas, yaitu kerugian besar bagi kita, umat Islam, kalau mengesampingkan pemikiran-pemikiran tokoh ini.
Bagaimanapun juga, pemikiran politik Ibn Taimiyah memiliki relevansi yang jelas dengan zaman modern. Dengan mengkaji pemikiran-pemikirannya diharapkan banyak kesimpangsiuran bisa dihilangkan dari pemikiran politik di dunia Islam pada masa kini. Studi yang dinamis dan kritis terhadap pemikiran politik Ibn Taimiyah sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini.
B. Biografi Ibn Taimiyah
Ibn Taimiyah memiliki nama lengkap Abu Abbas Ahmad bin Abd Halim bin Abd al-Salam Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah. Ia lahir di Harran, Syria pada hari senin 10 Rabiul Awal tahun 661 H/22 Januari 1263 M. dan wafat di Damaskus pada malam senin, 20 Zulkaidah 728 H/26 September 1328 M.[2]
Ibn Taimiyah lahir dari sebuah keluarga terpelajar dan sangat Islami serta dihormati dan disegani oleh masyarakat luas pada zamannya. Ayahnya, Syihab al-Din Abdul Halim ibn Abd as-Salam, adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Masjid Agung Damaskus. Kakeknya, syekh Majd ad-Din Abi al-Barakat Abd as-salam ibn Abd Allah juga seorang 'alim terkenal yang ahli tafsir, ahli hadis, ahli ushul fiqh, ahli nahwu, dan pengarang. Pamannya dari pihak bapak, Syaraf ad-Din Abd Allah ibn Abd al-Halim adalah seorang cendekiawan Muslim populer dan pengarang yang produktif pada masanya. Sedangkan adik laki-lakinya ternyata juga dikenal sebagai ilmuan Muslim yang ahli dalam bidang kewarisan Islam, ilmu-ilmu hadis dan ilmu pasti.[3]
Di samping belajar dan berguru kepada ayah dan pamannya, Ibn Taimiyah juga belajar kepada sejumlah ulama terkemuka seperti Syams ad-Din Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Ahmad al-Maqdisi, seorang faqih ternama dan hakim agung pertama dari kalangan mazhab Hambali di Syria, Muhammad ibn Abd al-Qawi ibn Badran al-Maqdisi al-Mardawi, seorang muhaddis, faqih, nahwiyy, dan mufti serta pengarang terpandang pada masanya, al-Manja' ibn Usman ibn asy-Syaibani. Selain itu, Ibn Taimiyah juga berguru kepada Zainab binti Makki al-Harrani, Syekh Syams ad-Din al-Asfihani asy-Syafi'i, Abd ar-Rahim ibn Muhammad al-Bagdadi, dan sejumlah ulama lain, baik yang terbilang kecil maupun tergolong besar, yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan orang.[4]
Pada masa Ibn Taimiyah hidup, Islam sedang mengalami kemunduran. Di sebelah Timur, kaum Muslimin dikalahkan dan dihancurekan tentara Mongol, dan di sebelah Barat mereka akhirnya terusir dari Spanyol. Akibatnya banyak kaum cerdik pandai mengungsi ke negeri-negeri yang lebih aman seperti ke Kairo dan Damaskus. Termasuk yang mengungsi adalah keluarga Ibn Taimiyah. Di Damaskus, keluarga Ibn Taimiyah kemudian menjadi tokoh-tokoh terkemuka karena pengabdian mereka kepada ilmu pengetahuan Islam.[5]
Setelah menguasai ilmu yang memadai, bahkan lebih dari itu, Ibn Taimiyah, yang telah menjadi mufti sejak sebelum berumur 20 tahun itu, mengabdikan ilmunya demi kepentingan Islam dan umat penganutnya. Sewaktu ayahnya wafat pada tahun 682 H/1284 M., ia yang waktu itu belum menamatkan studi formalnya dalam usia 21 tahun, menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai Direktur Madrasah Dar al-Hadis as-Syukkariyah. Selain itu, Ibn Taimiyah juga harus menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadis dan fiqh Hambali di beberapa madrasah terkenal yang ada di Damaskus. Mulai dari sinilah karir Ibn Taimiyah selalu meningkat dari tahun ke tahun, sejak dari 'alim kelas lokal dan kemudian nasional sampai akhirnya menjadi ulama besar yang berkaliber regional dan bahkan internasional.[6]
Dalam hal keagamaan, pada masa Ibn Taimiyah terdapat empat mazhab fiqh besar yang dijadikan rujukan umat Islam dan sudah sangat established, yaitu mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dalam hal teologi, paham al-Asy'ari dan al-Maturidi sangat mendominasi. Pada masa itu pula, muncul banyak tokoh-tokoh mistik dengan akrobatik-akrobatik spiritual mereka yang terlampau yakin dengan penafsiran bid'ah mereka, taqlid mutlak di dalam masalah-masalah kepercayaan, di dalam metode pemahaman, dan di dalam menerima hukum-hukum syari'ah beserta kesimpulan-kesimpulannya.[7] Dalam kondisi yang demikian Ibn Taimiyah mengumandangkan kebebasan berijtihad, dan anjuran untuk kembali kepada al-Qur'an, sunnah dan praktik-praktik as-salaf as-salih. Oleh sebab itu, maka konflik tidak bisa dihindarkan dengan para penentang-penentangnya yang tidak sepaham dengannya dan merasa terancam eksistensinya.
Konflik awal dalam masalah keagamaan antara Ibn Taimiyah dan para penentangnya adalah ketika orang-orang Hamah meminta pendapat (fatwa) nya mengenai sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Ibn Taimiyah memberikan jawaban dalam bentuk risalah yang berjudul ar-Risalah al-Hamawiyah. Risalah inilah yang memicu protes para fuqaha yang diketuai Qadhi Jalaluddin dari mazhab Hanafi di Damaskus. Ibn Taimiyah dihadapkan kepada para hakim dan ahli hukum terkemuka untuk mempertanggungjawabkan fatwa tersebut. Terjadilah perdebatan sengit yang akhirnya dimenangkan oleh Ibn Taimiyah. Peristiwa ini merupakan awal dari konflik intelektual yang seru di kemudian hari.[8]
Sementara awal keterlibatan Ibn Taimiyah dalam masalah politik adalah ketika ia memprotes keras keputusan pemerintah (Gubernur Siria) yang tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Assaf an-Nasrani, seorang Kristen berkebangsaan Suwayda', padahal Assaf telah menghina Nabi Muhammad saw. Hanya karena Assaf mau memeluk agama Islam ketimbang dijatuhi hukuman mati. Menurut Ibn Taimiyah, siapapun yang telah menghina Rasulullah, tidak peduli ia Muslim atau bukan, harus dihukum mati. Karena protes dan sikap tegasnya itu akhirnya Ibn Taimiyah harus meringkuk di dalam penjara 'Adrawiyyah di Damaskus.[9]
Walhasil, sesungguhnya dalam diri Ibn Taimiyah terkumpul kualitas manusia unggul seperti mujaddid, seorang egalitarianisme radikal, orator dan agitator ulung, dan panglima yang gagah berani. Hanya saja sikapnya yang menentang arus membuatnya banyak 'dimusuhi' oleh ulama-ulama lainnya. Menurut Qomaruddin Khan alasan utama munculnya tantangan terhadap pendapat-pendapat Ibn Taimiyah terutama sekali karena ia tidak dapat mengendalikan amarahnya, sering mengucapkan kata-kata yang pedas, dan bertekad akan menyerang musuh-musuhnya, meskipun menurut Khan, sifat Ibn Taimiyah tersebut lebih disebabkan polemik-polemik yang menyakitkan hatinya.[10]
Melihat sepak terjang dan pemikiran-pemikirannya seyogyanya Ibn Taimiyah sangat populer di kalangan umat Islam seluruhnya, sejajar dengan tokoh-tokoh Muslim lain yang sangat populer seperti al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Rusyd dan lain sebagainya. Tapi kenapa Ibn Taimiyah tidak sepopuler yang semestinya? Tampaknya di antara sebab-sebab yang membuat ia tidak setenar yang seharusnya adalah Ibn Taimiyah tergolong profil ulama dengan gaya pemikiran dan tulisan yang amat polemis, pendapatnya sangat kontroversial dan selalu menentang arus utama, di samping itu, ia juga merupakan tokoh aktiivis sosial dan kegamaan yang radikal dengan pikiran-poikiran orisinal yang pada masanya sukar atau belum waktunya bisa dipahami oleh umum.[11]
C. Pemikiran Politik Ibn Taimiyah
Pemikiran politik Ibn Taimiyah yang penting bisa ditemukan dalam karya-karyanya antara lain: Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah. Buku ini ditulis untuk mengkounter karya Ibn al-Muthahhar al-Hilli, buku yang lain adalah Minhaj al-Karamah fi Ma'rifat al-Imamah, kemudian al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah, meskipun buku ini lebih banyak berisi peraturan-peraturan administrasi Islam ketimbang politik, namun di dalamnya dapat kita temukan ide-ide yang sangat penting mengenai politik. Karya lainnya adalah al-Hisbah fi al-Islam. Dalam buku ini dijumpai pernyataan-pernyataan mengenai hakekat dan fungsi negara. Tulisan-tulisan lainnya berserakan dalam bentuk risalah dalam rangka polemiknya dengan para penentangnya. Salah seorang muridnya, Ibn al-Qayyim, menulis buku berjudul al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah. Namun, buku ini lebih banyak membahas prosedur pengadilan daripada teori politik atau pemerintahan.
Sementara buku yang ditulis sarjana Barat mengenai Ibn Taimiyah adalah karya Henry Laoust dalam bahasa Perancis berjudul "Les Doctrines Sociales et Politiques d' Ibn Taymiyyah". Buku ini merupakan studi paling serius dan teliti mengenai Ibn Taimiyah. Buku yang lebih merupakan karya ensiklopedis mengenai Ibn Taimiyah ini ditulis dengan menggunakan kerangka ilmiah dan sangat metodologis, meski sangat sering mengandung prasangka orientalis.[12] Sayang sekali buku ini tidak sampai kepada penulis baik dalam bentuk aslinya maupun tarjamahannya.
Untuk mengetahui pokok-pokok pemikiran politik Ibn Taimiyah dan supaya lebih mudah memahaminya akan kami paparkan dalam bentuk pointer-pointer sebagai berikut:
1. Asal Usul dan Sifat Negara
a. Menegakkan Negara
Pemikir-pemikir Muslim memandang masalah ini dalam bentuk yang berbeda-beda. Kaum Sunni menyatakan bahwa menegakkan negara (imamah) bukanlah salah satu asas dan praktik agama seperti yang diyakini oleh orang-orang Syi'ah. Menurut mereka, imamah adalah salah satu dari detail-detail (furu') yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang beriman, karena menurut pendapat mereka, kepada ummah diperintahkan untuk mengangkat seorang imam melalui al-sam' (tradisi).[13] Yang dimaksud dengan al-sam', menurut Qomaruddin Khan, adalah al-Qur'an , sunnah dan ijma'.[14]
Pandangan golongan Mu'tazilah sangat bertentangan dengan pandangan Sunni. Mu'tazilah berpendapat bahwa keharusan menegakkan imamah dapat dibuktikan oleh akal pikiran.[15] Sementara golongan Syi'ah juga menolak akal pikiran karena dianggap tidak mencukupi. Mereka berpendapat bahwa imamah adalah "lutf" (berkah) Allah kepada hamba-hamba-Nya.[16]
Ibn Taimiyah sendiri lebih sependapat dengan Sunni. Ia menyatakan bahwa mengatur urusan-urusan umat termasuk kewajiban-kewajiban agama yang terpenting. Tetapi tidak berarti agama tidak bisa tegak tanpa adanya negara. Kepentingan manusia, menurutnya, tidak bisa terpenuhi kecuali dengan bergabung menjadi suatu masyarakat, mengumpulkan kepentingan satu sama lain. Ketika berkumpul maka harus ada pemimpin.[17]
Ibn Taimiyah tidak mendasarkan pada metode ijma' sebagai alasan kewajiban mendirikan negara. Tetapi ia lebih menekankan kepada upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia (social welfare) dan melaksanakan syari'at Islam (iqamat al-Syari'ah al-Islamiyyah). Dengan demikian, sebetulnya Ibn Taimiyah tidak menganggap penting sistem khilafah. Menurutnya, institusi khilafah boleh ditiadakan, yang penting tujuan-tujuan positif bisa dicapai.
Sedemikian yakinnya Ibn Taimiyah terhadap keharusan otoritas negara sehingga ia mengatakan bahwa sesungguhnya raja adalah bayangan Allah di atas bumi, dan uangkapannya yang lain bahwa enam puluh tahun di bawah kekuasaan imam yang tiran itu lebih baik daripada satu malam tanpa seorang imam (chaos/vacuum of power).[18] Agaknya dalam hal ini Ibn Taimiyah lebih suka menggunakan teori stabilitas.
b. Pengangkatan Kepala Negara
Ibn Taimiyah tidak secara tegas merumuskan mekanisme pengangkatan kepala negara. Dia hanya menyebutkan bahwa sebetulnya tidak terlalu penting membicarakan sistem pengangkatan kepala negara. Menurutnya, yang penting adalah bahwa orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar amanah dan adil.[19] Karena pentingnya dua hal ini, sehingga di awal bukunya, al-Siyasah al-Syari'yah, ia secara khusus membahas doktrin amanah dan keadilan bagi mereka yang menduduki jabatan. Ibn Taimiyah mensyaratkan dua hal bagi kepala negara, yaitu memiliki kualifikasi kekuatan (al-quwwah) dan integritas (al-amanat).[20]
Kekuatan dan integritas ini menurut Ibn Taimiyah diperoleh melalui cara mubaya'ah yang diberikan oleh ahl al-Syawkah[21] yang efektif kepada raja/kepala negara. Ini berarti bahwa dukungan umat muncul sebagai akibat wajar dari bay'ah tersebut, bukan sebagai prosedur terpisah yang diperlukan itu sendiri. Mubaya'ah ini nantinya akan berfungsi menjadi semacam kontrak sosial yang mengikat antara raja/kepala negara dan rakyat. Sedangkan yang dimaksud ahl al-Syawkah sendiri menurut Ibn Taimiyah adalah semua orang, tanpa memandang profesi dan kedudukan mereka, dihormati dan ditaati oleh masyarakat[22]. Barangkali pada zaman sekarang ini ahl al-Syawkah bisa ndisamakan dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
Menurut Qomaruddin Khan hanya Ibn Taimiyahlah yang telah memberikan perspektif yang tepat kepada konsep syawkah ini. Ibn Taimiyah menolak teori tradisional mengenai kekhalifahan dan mengembangkan sebuah teori tersendiri mengenai negara. Konsep atau teori ini pada gilirannya nanti ditransformasikan oleh Ibnu Khaldun ke dalam teorinya yang terkenal mengenai 'asabiyah.[23]
Meskipun Ibn Taimiyah mensyaratkan dua hal kepada calon penguasa atau kepala negara, namun apabila penguasa atau kepala negara yang ideal (memiliki kualifikasi kekuatan dan integritas) tidak bisa diperoleh, menurut Ibn Taimiyah harus diangkat orang yang paling sesuai untuk pekerjaan itu. Tetapi, menurutnya hal itu hanya bersifat sementara, dan bahwa setelah itu kaum Muslim harus berusaha memperbaiki keadaan mereka supaya dapat memenuhi ajaran-ajaran Islam.[24]
Dalam hal penunjukan atau pengangkatan pembantu-pembantunya, Ibn Taimiyah berpendapat, bahwa seorang kepala negara harus berusaha mencari orang-orang yang secara objektif betul-betul memiliki kecakapan dan kemampuan untuk jabatan-jabatan tersebut, dan jangan karena terpengaruh faktor-faktor subjektif seperti hubungan kekeluargaan dan lain sebagainya.
Tampaknya Ibn Taimiyah memaknai kata amanah dalam dua pengertian. Pertama, amanah diartikan kepentingan-kepentingan rakyat yang merupakan tanggung jawab kepala negara untuk mengelolanya. Kedua, amanah diartikan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh kepala negara.[25]
Dengan persyaratan yang demikian, maka Ibn Taimiyah tidak mensyaratkan calon kepala negara harus dari suku Quraisy. Persyaratan ini (suku Quraisy) bertentangan dengan al-Qur'an yang mengakui persamaan derajat sesama manusia, meskipun ada hadis yang dijadikan landasan terhadap persyaratan suku Quraisy tersebut.[26]
c. Tugas Kepala Negara
Tugas utama dan mendasar seorang kepala negara adalah menciptakan kemaslahatan bersama dalam wujud menjalankan amanah sebaik-baiknya dan menciptakan keadilan semaksimal mungkin. Dengan demikian, maka tujuan negara adalah 1) sebagai alat untuk menjalankan syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan umat manusia sebaik-baiknya, 2) berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan bersama secara hakiki, lahir dan batin seluruh rakyat, dan 3) merupakan lembaga yang harus bertanggung jawab dalam menjalankan amanah dan menciptakan keadilan.[27]
d. Bentuk Negara/Pemerintahan
Ibn Taimiyah lebih cenderung kepada bentuk pemerintahan demokratis. Pendapatnya ini disimpulkan dari penolakannya terhadap sistem khilafah dan juga terhadap model Syi'ah (imamah). Hanya saja demokratis yang dikehendaki Ibn Taimiyah adalah demokratis konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai syari'at[28]. Model seperti ini, menurut Ibn Taimiyah, bisa merealisasikan nilai-nilai keadilan. Bukankah Allah mengirimkan utusan-utusan-Nya supaya kita bersikap adil baik berhubungan dengan hak-hak Allah maupun dengan hak-hak manusia sebagaimana firman-Nya:
…Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya rela mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan Rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak melihatnya.[29]
2. Negara Nubuwwah dan Khilafah Nubuwwah
Tesis pokok Ibn Taimiyah mengenai negara kenabian adalah bahwa Nabi Muhammad saw. hanyalah seorang Nabi, bahwa segala aktifitasnya tercakup ke dalam fungsi kenabiannya, dan bahwa institusi imamah tidak berada di luar fungsi tersebut dan tidak pula merupakan rukun iman.[30] Pada masa Nabi masih hidup imamah tidak diperlukan, konsep imamah muncul setelah wafatnya Nabi. Ibn Taimiyah memiliki alasan-alasan yang kuat untuk membedakan rejim nubuwwah dengan negara Islam yang lahir setelah Muhammad meninggal dunia. Seorang raja, menurutnya, kepatuhan rakyat kepadanya karena ia adalah seorang raja. Tetapi, kita tentu menyadari bahwa Muhammad harus dipatuhi bukan karena dia seorang kepala negara tetapi karena dia adalah Rasul Allah.[31]
Sebenarnya inti tesis Ibn Taimiyah di atas dikarenakan pertama, penyangkalannya terhadap teori ilahiah mengenai imamah yang dikemukakan kaum Syi'ah, sedang ia tidak menyangkal fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad adalah seorang imam yang sejati. Kedua, menurutnya, kaum Muslimin tidak pernah mementingkan sesuatupun juga melebihi iman. Ketiga, bahwa detail-detail penataan negara tidak perlu disebutkan di dalam al-Qur'an. Negara, menurutnya, harus dinamis dan progresif di dalam sifat dan kondisinya.[32]
Berkaitan dengan khilafah Nubuwwah, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa perkataan khilafah, seperti terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah, tidak mengandung signifikansi religius dan politik.[33] Mengenai empat sahabat (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali), Ibn Taimiyah lebih suka menyebtunya sebagai khalifah an-Nubuwwah.[34]
Menurut penulis persoalan apakah perkataan khilafah di dalam al-Qur'an maupun hadits mengandung signifikansi religius dan politik atau tidak memang masih menjadi perdebatan, bahkan kalau Ibn Taimiyah telah secara tegas menyatakan tidak. Tetapi bahwa khilafah itu pernah ada dalam sejarah perpolitikan Islam terlepas dari sebutan yang digunakan sebagai penggantinya juga merupakan sesuatu yang tidak bisa terbantahkan dan hal ini juga diakui oleh Ibn Taimiyah. Menurutnya khilafah pernah ada di dalam sejarah sebagai sebuah institusi politik.
D. Implikasi Pemikiran Politik Ibn Taimiyah Terhadap Pemikiran Politik Islam Modern
Ibn Taimiyah yang bermadzhab Hambali dalam banyak—meskipun tidak semua—perkara hukum dan teologis, dan seorang penganut Salafiyah pada bidang yang lebih luas, sangat berpengaruh kuat di kalangan Sunni konservatif dan, dalam periode modern, di kalangan kaum liberal dan konservatif. Sejumlah gagasan Ibn Taimiyah relevan dengan masyarakat dan politik karena menurutnya agama dan negara berkaitan erat (al-Islam al-din wa al-daulah). Gagasan-gagasannya tersebut ada yang bermakna positif tapi banyak juga yang berimplikasi negatif. Di antara gagasannya yang berimplikasi negatif misalnya, dia mendefinisikan orang Mongol sebagai kafir walaupun mereka memiliki wacana Islam publik. Dia memiliki antipati umum kepada ahl al-kitab.[35]
Pemikiran takfir semacam ini, di zaman modern, banyak diikuti oleh gerakan-gerakan militan-radikal seperti tampak pada pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna dan sayyid Qutb dengan konsepnya yang terkenal "jahiliyah modern". Pemikiran Ibn Taimiyah juga menjadi inspirasi bagi Muhammad Abd al-Salam Faraj, juru bicara intelektual dari kelompok yang merekayasa pembunuhan atas Anwar Sadat. Dalam sebuah risalahnya yang berjudul al-Risalah al-Faridhah, ia mengutip fatwa Ibn Taimiyah tentang orang Mongol sebagai preseden dalam takfirnya terhadap penguasa dan otoritas religius kontemporer.[36]
Implikasi positif dari pemikiran politik Ibn Taimiyah misalnya dalam hal pemahamannya yang tidak kaku terhadap konsep khilafah. Menurutnya, model negara boleh apa saja asalkan bisa merealisasikan tujuan-tujuan sebuah negara, yaitu kemaslahatan umat manusia, menciptakan keadilan dan menegakkan syari'at Allah. Berkaitan dengan konsep kepala negara (khalifah), Ibn Taimiyah memberi peluang bagi adanya pluralisme dalam dunia Islam. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa umat Islam tidak harus mempunyai hanya seorang khalifah, tetapi dibolehkan adanya beberapa khalifah dan beberapa negara yang menjadi daerah kekuasaan masing-masing khalifah itu.[37] Pandangan yang cukup realistis mengingat pada masa Ibn Taimiyah secara de facto tidak hanya terdiri dari satu kekhalifahan, tetapi terdiri dari lebih satu kekhalifahan dan beberapa kerajaan atau dinasti.
Menurut penulis banyak orang yang menjadikan pendapat atau pemikiran Ibn Taimiyah sebagai sandaran dalam tindakannya yang negatif karena ketidakmengertian atau paling tidak telah terjadi kesalahan dalam memahami pemikiran Ibn Taimiyah walaupun dalam kasus-kasus tertentu penulis juga sependapat bahwa ada pemikiran Ibn Taimiyah yang berpotensi menimbulkan hal-hal baik pandangan maupun sikap yang negatif dan merugikan.
E. Penutup
Pemikiran politik seseorang memang akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosio-religius di mana seseorang tinggal dan berinteraksi, termasuk pemikiran politik Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah yang hidup pada masa dunia Islam sedang mengalami puncak disintegrasi poltiik, dislokasi sosial dan dekadensi akhlak serta moral jelas sangat berpengaruh terhadap model pemikiran-pemikiran politiknya. Jika demikian halnya, maka konsep takfirnya terhadap orang-orang Mongol, meskipun sudah masuk Islam, bisa dipahami. Apalagi dia dan keluarganya harus mengungsi ke Damaskus karena serangan tentara Tartar yang sangat bengis dan kejam.
Pemikiran politik Ibn Taimiyah begitu amat penting di dalam sejarah politik Islam, bahkan hingga saat ini. Tesisnya yang mengatakan bahwa rejim yang ditegakkan Nabi adalah rejim nubuwwah dan bukan imamah, sedang imamah baru ada setelah Nabi wafat, perlu senantiasa dikaji. Wallahu 'A'lam.
DAFTAR PUSTAKA
Amin, Muhammad, Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fikih Islam, Jakarta: INIS, 1991.
Esposito, John L., Ensiklopedi Oxford-Dunia Islam Modern, penerj. Eva Y.N., Femmy Syahrani, Jarot W., Poerwanto, Rofik S., cet. 1. Bandung: Mizan, 2001.
Hamadah, Abdul Ghani, Fadh al-Dzakirin wa al-Raddu 'Ala al-Munkirin. Suria: t.p., 1971.
Katsir, Ibn, al-Bidayah wa an-Nihayah, jilid IX juz 14. Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, t.th.
Khan, Qomaruddin, The Political Thought of Ibn Taimiyah, 2nd edition. Pakistan: Islamic Research Institute, 1985.
Madjid, Nurcholish, Khazanah Intelektual Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
Rojak, Jeje Abdul, Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah, cet. 1. Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara Ajaran , Sejarah dan Pemikiran, edisi 5. Jakarta: UI Press, 1993.
Taimiyah, Ibn, al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyyah, cet. 2. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1951.
---------, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah, jilid 1. Kairo: Maktabah Dar al-'Urubat, 1962.
---------, Majmu' Rasail, al-Hisbah. Kairo: t.tp., 1323.
[1] Hal ini tidak terlepas dari proyek besar Ibn Taimiyah yang ingin memberantas praktik-praktik bid'ah, khurafat, tahayul dan mistik yang menurutnya menjadi pangkal penyebab kemunduran dan kejatuhan Islam dan umat Islam.
[2] Ibn Katsir, al-Bidayah wa an-Nihayah, jilid IX juz 14, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, t.th), halm. 135-136. Lihat juga Muhammad Amin, Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fikih Islam, (Jakarta: INIS, 1991), halm. 7.
[3] Amin, Ijtihad, halm. 7-8.
[4] Ibid., halm. 9-10.
[5] Qomaruddin Khan, The Political Thought of Ibn Taimiyah, 2nd edition, (Pakistan: Islamic Research Institute, 1985), halm. 2.
[6] Amin., Ijtihad, halm. 12.
[7] Khan, The Political, halm. 5-6.
[8] Ibid., halm. 7. Konflik selanjutnya misalnya dengan kaum sufi yang disponsori Ibn 'Ata' as-Sukandari. Untuk mengetahui komentar-komentar penentangnya, penulis kutipkan pernyataan al-ustadz Abdul Ghani Hamadah. Ia menyatakaan bahwa orang-orang ahli bid'ah mengagungkan dirinya sendiri. Mereka berkata kami adalah peniolong sunnah, kami salafiyun, kami mujaddidun sebagaimana yang dikatakan oleh guru mereka, Ibn Taimiyah. Padahal sebenarnya merekalah ahli bid'ah dari golongan yang sesat karena 1) penyimpangan mereka dari imam mazhab yang empat dan dari jumhur ulama kaum Muslimin, 2) paham antrophomorpisme/tajsim mereka terhadap sifat-sifat Allah, dan 3) mengkafirkan ulama-ulama dan auliya terkemuka. Hamadah juga mengutip komentar-komentar ulama mengenai diri Ibn Taimiyah, mislanya 'Alauddin al-Bukhari mengatakan bahwa Ibn Taimiyah kafir, Zainuddin al-Hambali menyebutnya kafir, imam as-Subki mengkafirkan Ibn Taimiyah karena ia telah mengkafirkan umat Islam dan menyerupakan mereka dengan kaum Yahudi dan Nasrani di dalam tafsirnya, Ibn Hajar menyebut Ibn Taimiyah sebagai hamba yang ditelantarkan, disesatkan, dibutakan, dibisukan, dan dihinakan Allah dan komentar-komentar ulama lainnya. Periksa al-Ustadz Abdul Ghani Hamadah, Fadh al-Dzakirin wa al-Raddu 'Ala al-Munkirin (Suria: t.p., 1971), halm. 22-23.
[9] Amin, Ijtihad, halm. 13.
[10] Khan, The Political,halm. 5.
[11] Jeje Abdul Rojak, Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah, cet. 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), halm. 126.
[12] Khan, "Pendahuluan", halm. ii.
[13] Ibn Taimiyah, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah, jilid 1 (Kairo: Maktabah Dar al-'Urubat, 1962), halm. 26.
[14] Khan, The Political,halm. 24.
[15] Ibid., halm. 25.
[16] Ibid., halm. 28.
[17] Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyyah, cet. 2 (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1951), halm. 172-173.
[18] Ibid., halm. 173.
[19] Disebutkan bahwa Allah menolong pemerintahan yang adil walaupun yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan tidak menolong pemerintahan yang sewenang-wenang walaupun yang dimiliki oleh orang-orang Muslim. Lihat Ibn Taimiyah, Majmu' Rasail, al-Hisbah (Kairo: t.tp., 1323), halm. 36. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa sehari bersama seorang pemimpin yang adil itu lebih utama daripada beribadah enam puluh tahun. Lihat juga Ibn Taimiyah, al-Siyasah, halm. 22.
[20] Ibid., halm. 20.
[21] Konsep ahl al-Syawkah yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah berbeda dengan konsep yang pernah diajukan oleh al-Ghazali. Menurut al-Ghazali ahl al-Syawkah adalah para penguasa yang sedang berkuasa pada masanya. Dalam konteks al-Ghazali yang dimaksud adalah para penguasa Turki dari Dinasti Saljuq yang menjadi penguasa di kota Baghdad.
[22] Khan, The Political,halm. 234.
[23] Khan, The Political halm. 235.
[24] Ibn Taimiyah, As-Siyasah, halm. 13-21.
[25] Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran , Sejarah dan Pemikiran, edisi 5. (Jakarta: UI Press, 1993), halm. 85-86.
[26] Pendapat Ibn Taimiyah ini bertentangan dengan pendapatnya sendiri yang tertuang dalam bukunya, Minhaj. Ia menerangkan syarat-syarat di dalam pemilihan seorang imam, yaitu: 1) harus dari suku Quraisy, 2) harus diangkat melalui konsultasi di antara orang-orang Muslim, 3) harus mendapatkan sumpah setia dari orang-orang Muslim, dan 4) harus bersifat adil. Periksa Ibn Taimiyah, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Naqd Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah, jilid 2. (Kairo: Maktabah Dar al-'Urubat, 1962), halm. 86-89.
[27] Rojak, Politik, halm. 166-167.
[28] Ibid., halm. 179. Tampaknya pemikiran Ibn Taimiyah ini di kemudian hari menjadi inspirasi bagi Sayyid Abu A'la Maududi untuk menyusun teori politiknya. Menurut Maududi sistem politik Islam bukan teokrasi dan bukan pula demokrasi sebagaimana di Barat. Menurutnya sistem politik Islam lebih merupakan perpaduan antara keduanya sehingga bisa disebut dengan teo-demokrasi. Lebih lengkapnya lihat Maududi, Political Theory of Islam, (Lahore: Islamic Publications Limited, 1960).
[29] Al-Qur'an, 57:25.
[30] Khan, The Political,halm. 54.
[31] Ibid., halm. 57-58.
[32] Ibid., halm. 56.
[33] Ibid., halm. 137.
[34] Ibid., halm. 146.
[35] John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford-Dunia Islam Modern, penerj. Eva Y.N., Femmy Syahrani, Jarot W., Poerwanto, Rofik S., cet. 1 (Bandung: Mizan, 2001), halm. 244.
[36] Ibid., halm. 245.
[37] Nurcholish Madjid, Khazanah Intelektual Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), halm. 42.
Oleh: A. Saifuddin
A. Pendahuluan
Ketika mendengar dan berbicara tentang sosok Ibn Taimiyah, maka terbersit di ingatan penulis komentar-komentar para kiyai dan ustadz ketika masih di pondok pesantren bahwa tokoh yang satu ini meskipun 'alim tapi karena banyak menghujat dan bahkan mengkafirkan para ulama, ia dianggap kafir, zindiq, dan term-term semacamnya.[1] Akibatnya tokoh ini tidak begitu dikenal (dimajhulkan) di kalangan pesantren yang begitu kuat memegangi tradisi ahl al-sunnah wa al-jama'ah. Tidak mengherankan pula jika penulis yang dibesarkan di kalangan pesantren baru sedikit mengetahui tokoh ini ketika sudah di bangku kuliah.
Namun, terlepas dari kontroversi sosok seorang Ibn Taimiyah, menurut penulis, tidak bijak jika kemudian melupakan dan tidak mau mempelajari pemikiran-pemikirannya, terutama yang berkaitan dengan politik—sebagai bidang yang menonjol ia bahas—karena sikap a-priori dan asumsi-asumsi yang kita bangun belum tentu sepenuhnya mengandung kebenaran. Sebaliknya, akibat yang ditimbulkan adalah sangat jelas, yaitu kerugian besar bagi kita, umat Islam, kalau mengesampingkan pemikiran-pemikiran tokoh ini.
Bagaimanapun juga, pemikiran politik Ibn Taimiyah memiliki relevansi yang jelas dengan zaman modern. Dengan mengkaji pemikiran-pemikirannya diharapkan banyak kesimpangsiuran bisa dihilangkan dari pemikiran politik di dunia Islam pada masa kini. Studi yang dinamis dan kritis terhadap pemikiran politik Ibn Taimiyah sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini.
B. Biografi Ibn Taimiyah
Ibn Taimiyah memiliki nama lengkap Abu Abbas Ahmad bin Abd Halim bin Abd al-Salam Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah. Ia lahir di Harran, Syria pada hari senin 10 Rabiul Awal tahun 661 H/22 Januari 1263 M. dan wafat di Damaskus pada malam senin, 20 Zulkaidah 728 H/26 September 1328 M.[2]
Ibn Taimiyah lahir dari sebuah keluarga terpelajar dan sangat Islami serta dihormati dan disegani oleh masyarakat luas pada zamannya. Ayahnya, Syihab al-Din Abdul Halim ibn Abd as-Salam, adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Masjid Agung Damaskus. Kakeknya, syekh Majd ad-Din Abi al-Barakat Abd as-salam ibn Abd Allah juga seorang 'alim terkenal yang ahli tafsir, ahli hadis, ahli ushul fiqh, ahli nahwu, dan pengarang. Pamannya dari pihak bapak, Syaraf ad-Din Abd Allah ibn Abd al-Halim adalah seorang cendekiawan Muslim populer dan pengarang yang produktif pada masanya. Sedangkan adik laki-lakinya ternyata juga dikenal sebagai ilmuan Muslim yang ahli dalam bidang kewarisan Islam, ilmu-ilmu hadis dan ilmu pasti.[3]
Di samping belajar dan berguru kepada ayah dan pamannya, Ibn Taimiyah juga belajar kepada sejumlah ulama terkemuka seperti Syams ad-Din Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Ahmad al-Maqdisi, seorang faqih ternama dan hakim agung pertama dari kalangan mazhab Hambali di Syria, Muhammad ibn Abd al-Qawi ibn Badran al-Maqdisi al-Mardawi, seorang muhaddis, faqih, nahwiyy, dan mufti serta pengarang terpandang pada masanya, al-Manja' ibn Usman ibn asy-Syaibani. Selain itu, Ibn Taimiyah juga berguru kepada Zainab binti Makki al-Harrani, Syekh Syams ad-Din al-Asfihani asy-Syafi'i, Abd ar-Rahim ibn Muhammad al-Bagdadi, dan sejumlah ulama lain, baik yang terbilang kecil maupun tergolong besar, yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan orang.[4]
Pada masa Ibn Taimiyah hidup, Islam sedang mengalami kemunduran. Di sebelah Timur, kaum Muslimin dikalahkan dan dihancurekan tentara Mongol, dan di sebelah Barat mereka akhirnya terusir dari Spanyol. Akibatnya banyak kaum cerdik pandai mengungsi ke negeri-negeri yang lebih aman seperti ke Kairo dan Damaskus. Termasuk yang mengungsi adalah keluarga Ibn Taimiyah. Di Damaskus, keluarga Ibn Taimiyah kemudian menjadi tokoh-tokoh terkemuka karena pengabdian mereka kepada ilmu pengetahuan Islam.[5]
Setelah menguasai ilmu yang memadai, bahkan lebih dari itu, Ibn Taimiyah, yang telah menjadi mufti sejak sebelum berumur 20 tahun itu, mengabdikan ilmunya demi kepentingan Islam dan umat penganutnya. Sewaktu ayahnya wafat pada tahun 682 H/1284 M., ia yang waktu itu belum menamatkan studi formalnya dalam usia 21 tahun, menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai Direktur Madrasah Dar al-Hadis as-Syukkariyah. Selain itu, Ibn Taimiyah juga harus menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadis dan fiqh Hambali di beberapa madrasah terkenal yang ada di Damaskus. Mulai dari sinilah karir Ibn Taimiyah selalu meningkat dari tahun ke tahun, sejak dari 'alim kelas lokal dan kemudian nasional sampai akhirnya menjadi ulama besar yang berkaliber regional dan bahkan internasional.[6]
Dalam hal keagamaan, pada masa Ibn Taimiyah terdapat empat mazhab fiqh besar yang dijadikan rujukan umat Islam dan sudah sangat established, yaitu mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dalam hal teologi, paham al-Asy'ari dan al-Maturidi sangat mendominasi. Pada masa itu pula, muncul banyak tokoh-tokoh mistik dengan akrobatik-akrobatik spiritual mereka yang terlampau yakin dengan penafsiran bid'ah mereka, taqlid mutlak di dalam masalah-masalah kepercayaan, di dalam metode pemahaman, dan di dalam menerima hukum-hukum syari'ah beserta kesimpulan-kesimpulannya.[7] Dalam kondisi yang demikian Ibn Taimiyah mengumandangkan kebebasan berijtihad, dan anjuran untuk kembali kepada al-Qur'an, sunnah dan praktik-praktik as-salaf as-salih. Oleh sebab itu, maka konflik tidak bisa dihindarkan dengan para penentang-penentangnya yang tidak sepaham dengannya dan merasa terancam eksistensinya.
Konflik awal dalam masalah keagamaan antara Ibn Taimiyah dan para penentangnya adalah ketika orang-orang Hamah meminta pendapat (fatwa) nya mengenai sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Ibn Taimiyah memberikan jawaban dalam bentuk risalah yang berjudul ar-Risalah al-Hamawiyah. Risalah inilah yang memicu protes para fuqaha yang diketuai Qadhi Jalaluddin dari mazhab Hanafi di Damaskus. Ibn Taimiyah dihadapkan kepada para hakim dan ahli hukum terkemuka untuk mempertanggungjawabkan fatwa tersebut. Terjadilah perdebatan sengit yang akhirnya dimenangkan oleh Ibn Taimiyah. Peristiwa ini merupakan awal dari konflik intelektual yang seru di kemudian hari.[8]
Sementara awal keterlibatan Ibn Taimiyah dalam masalah politik adalah ketika ia memprotes keras keputusan pemerintah (Gubernur Siria) yang tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Assaf an-Nasrani, seorang Kristen berkebangsaan Suwayda', padahal Assaf telah menghina Nabi Muhammad saw. Hanya karena Assaf mau memeluk agama Islam ketimbang dijatuhi hukuman mati. Menurut Ibn Taimiyah, siapapun yang telah menghina Rasulullah, tidak peduli ia Muslim atau bukan, harus dihukum mati. Karena protes dan sikap tegasnya itu akhirnya Ibn Taimiyah harus meringkuk di dalam penjara 'Adrawiyyah di Damaskus.[9]
Walhasil, sesungguhnya dalam diri Ibn Taimiyah terkumpul kualitas manusia unggul seperti mujaddid, seorang egalitarianisme radikal, orator dan agitator ulung, dan panglima yang gagah berani. Hanya saja sikapnya yang menentang arus membuatnya banyak 'dimusuhi' oleh ulama-ulama lainnya. Menurut Qomaruddin Khan alasan utama munculnya tantangan terhadap pendapat-pendapat Ibn Taimiyah terutama sekali karena ia tidak dapat mengendalikan amarahnya, sering mengucapkan kata-kata yang pedas, dan bertekad akan menyerang musuh-musuhnya, meskipun menurut Khan, sifat Ibn Taimiyah tersebut lebih disebabkan polemik-polemik yang menyakitkan hatinya.[10]
Melihat sepak terjang dan pemikiran-pemikirannya seyogyanya Ibn Taimiyah sangat populer di kalangan umat Islam seluruhnya, sejajar dengan tokoh-tokoh Muslim lain yang sangat populer seperti al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Rusyd dan lain sebagainya. Tapi kenapa Ibn Taimiyah tidak sepopuler yang semestinya? Tampaknya di antara sebab-sebab yang membuat ia tidak setenar yang seharusnya adalah Ibn Taimiyah tergolong profil ulama dengan gaya pemikiran dan tulisan yang amat polemis, pendapatnya sangat kontroversial dan selalu menentang arus utama, di samping itu, ia juga merupakan tokoh aktiivis sosial dan kegamaan yang radikal dengan pikiran-poikiran orisinal yang pada masanya sukar atau belum waktunya bisa dipahami oleh umum.[11]
C. Pemikiran Politik Ibn Taimiyah
Pemikiran politik Ibn Taimiyah yang penting bisa ditemukan dalam karya-karyanya antara lain: Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah. Buku ini ditulis untuk mengkounter karya Ibn al-Muthahhar al-Hilli, buku yang lain adalah Minhaj al-Karamah fi Ma'rifat al-Imamah, kemudian al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah, meskipun buku ini lebih banyak berisi peraturan-peraturan administrasi Islam ketimbang politik, namun di dalamnya dapat kita temukan ide-ide yang sangat penting mengenai politik. Karya lainnya adalah al-Hisbah fi al-Islam. Dalam buku ini dijumpai pernyataan-pernyataan mengenai hakekat dan fungsi negara. Tulisan-tulisan lainnya berserakan dalam bentuk risalah dalam rangka polemiknya dengan para penentangnya. Salah seorang muridnya, Ibn al-Qayyim, menulis buku berjudul al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah. Namun, buku ini lebih banyak membahas prosedur pengadilan daripada teori politik atau pemerintahan.
Sementara buku yang ditulis sarjana Barat mengenai Ibn Taimiyah adalah karya Henry Laoust dalam bahasa Perancis berjudul "Les Doctrines Sociales et Politiques d' Ibn Taymiyyah". Buku ini merupakan studi paling serius dan teliti mengenai Ibn Taimiyah. Buku yang lebih merupakan karya ensiklopedis mengenai Ibn Taimiyah ini ditulis dengan menggunakan kerangka ilmiah dan sangat metodologis, meski sangat sering mengandung prasangka orientalis.[12] Sayang sekali buku ini tidak sampai kepada penulis baik dalam bentuk aslinya maupun tarjamahannya.
Untuk mengetahui pokok-pokok pemikiran politik Ibn Taimiyah dan supaya lebih mudah memahaminya akan kami paparkan dalam bentuk pointer-pointer sebagai berikut:
1. Asal Usul dan Sifat Negara
a. Menegakkan Negara
Pemikir-pemikir Muslim memandang masalah ini dalam bentuk yang berbeda-beda. Kaum Sunni menyatakan bahwa menegakkan negara (imamah) bukanlah salah satu asas dan praktik agama seperti yang diyakini oleh orang-orang Syi'ah. Menurut mereka, imamah adalah salah satu dari detail-detail (furu') yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang beriman, karena menurut pendapat mereka, kepada ummah diperintahkan untuk mengangkat seorang imam melalui al-sam' (tradisi).[13] Yang dimaksud dengan al-sam', menurut Qomaruddin Khan, adalah al-Qur'an , sunnah dan ijma'.[14]
Pandangan golongan Mu'tazilah sangat bertentangan dengan pandangan Sunni. Mu'tazilah berpendapat bahwa keharusan menegakkan imamah dapat dibuktikan oleh akal pikiran.[15] Sementara golongan Syi'ah juga menolak akal pikiran karena dianggap tidak mencukupi. Mereka berpendapat bahwa imamah adalah "lutf" (berkah) Allah kepada hamba-hamba-Nya.[16]
Ibn Taimiyah sendiri lebih sependapat dengan Sunni. Ia menyatakan bahwa mengatur urusan-urusan umat termasuk kewajiban-kewajiban agama yang terpenting. Tetapi tidak berarti agama tidak bisa tegak tanpa adanya negara. Kepentingan manusia, menurutnya, tidak bisa terpenuhi kecuali dengan bergabung menjadi suatu masyarakat, mengumpulkan kepentingan satu sama lain. Ketika berkumpul maka harus ada pemimpin.[17]
Ibn Taimiyah tidak mendasarkan pada metode ijma' sebagai alasan kewajiban mendirikan negara. Tetapi ia lebih menekankan kepada upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia (social welfare) dan melaksanakan syari'at Islam (iqamat al-Syari'ah al-Islamiyyah). Dengan demikian, sebetulnya Ibn Taimiyah tidak menganggap penting sistem khilafah. Menurutnya, institusi khilafah boleh ditiadakan, yang penting tujuan-tujuan positif bisa dicapai.
Sedemikian yakinnya Ibn Taimiyah terhadap keharusan otoritas negara sehingga ia mengatakan bahwa sesungguhnya raja adalah bayangan Allah di atas bumi, dan uangkapannya yang lain bahwa enam puluh tahun di bawah kekuasaan imam yang tiran itu lebih baik daripada satu malam tanpa seorang imam (chaos/vacuum of power).[18] Agaknya dalam hal ini Ibn Taimiyah lebih suka menggunakan teori stabilitas.
b. Pengangkatan Kepala Negara
Ibn Taimiyah tidak secara tegas merumuskan mekanisme pengangkatan kepala negara. Dia hanya menyebutkan bahwa sebetulnya tidak terlalu penting membicarakan sistem pengangkatan kepala negara. Menurutnya, yang penting adalah bahwa orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar amanah dan adil.[19] Karena pentingnya dua hal ini, sehingga di awal bukunya, al-Siyasah al-Syari'yah, ia secara khusus membahas doktrin amanah dan keadilan bagi mereka yang menduduki jabatan. Ibn Taimiyah mensyaratkan dua hal bagi kepala negara, yaitu memiliki kualifikasi kekuatan (al-quwwah) dan integritas (al-amanat).[20]
Kekuatan dan integritas ini menurut Ibn Taimiyah diperoleh melalui cara mubaya'ah yang diberikan oleh ahl al-Syawkah[21] yang efektif kepada raja/kepala negara. Ini berarti bahwa dukungan umat muncul sebagai akibat wajar dari bay'ah tersebut, bukan sebagai prosedur terpisah yang diperlukan itu sendiri. Mubaya'ah ini nantinya akan berfungsi menjadi semacam kontrak sosial yang mengikat antara raja/kepala negara dan rakyat. Sedangkan yang dimaksud ahl al-Syawkah sendiri menurut Ibn Taimiyah adalah semua orang, tanpa memandang profesi dan kedudukan mereka, dihormati dan ditaati oleh masyarakat[22]. Barangkali pada zaman sekarang ini ahl al-Syawkah bisa ndisamakan dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
Menurut Qomaruddin Khan hanya Ibn Taimiyahlah yang telah memberikan perspektif yang tepat kepada konsep syawkah ini. Ibn Taimiyah menolak teori tradisional mengenai kekhalifahan dan mengembangkan sebuah teori tersendiri mengenai negara. Konsep atau teori ini pada gilirannya nanti ditransformasikan oleh Ibnu Khaldun ke dalam teorinya yang terkenal mengenai 'asabiyah.[23]
Meskipun Ibn Taimiyah mensyaratkan dua hal kepada calon penguasa atau kepala negara, namun apabila penguasa atau kepala negara yang ideal (memiliki kualifikasi kekuatan dan integritas) tidak bisa diperoleh, menurut Ibn Taimiyah harus diangkat orang yang paling sesuai untuk pekerjaan itu. Tetapi, menurutnya hal itu hanya bersifat sementara, dan bahwa setelah itu kaum Muslim harus berusaha memperbaiki keadaan mereka supaya dapat memenuhi ajaran-ajaran Islam.[24]
Dalam hal penunjukan atau pengangkatan pembantu-pembantunya, Ibn Taimiyah berpendapat, bahwa seorang kepala negara harus berusaha mencari orang-orang yang secara objektif betul-betul memiliki kecakapan dan kemampuan untuk jabatan-jabatan tersebut, dan jangan karena terpengaruh faktor-faktor subjektif seperti hubungan kekeluargaan dan lain sebagainya.
Tampaknya Ibn Taimiyah memaknai kata amanah dalam dua pengertian. Pertama, amanah diartikan kepentingan-kepentingan rakyat yang merupakan tanggung jawab kepala negara untuk mengelolanya. Kedua, amanah diartikan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh kepala negara.[25]
Dengan persyaratan yang demikian, maka Ibn Taimiyah tidak mensyaratkan calon kepala negara harus dari suku Quraisy. Persyaratan ini (suku Quraisy) bertentangan dengan al-Qur'an yang mengakui persamaan derajat sesama manusia, meskipun ada hadis yang dijadikan landasan terhadap persyaratan suku Quraisy tersebut.[26]
c. Tugas Kepala Negara
Tugas utama dan mendasar seorang kepala negara adalah menciptakan kemaslahatan bersama dalam wujud menjalankan amanah sebaik-baiknya dan menciptakan keadilan semaksimal mungkin. Dengan demikian, maka tujuan negara adalah 1) sebagai alat untuk menjalankan syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan umat manusia sebaik-baiknya, 2) berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan bersama secara hakiki, lahir dan batin seluruh rakyat, dan 3) merupakan lembaga yang harus bertanggung jawab dalam menjalankan amanah dan menciptakan keadilan.[27]
d. Bentuk Negara/Pemerintahan
Ibn Taimiyah lebih cenderung kepada bentuk pemerintahan demokratis. Pendapatnya ini disimpulkan dari penolakannya terhadap sistem khilafah dan juga terhadap model Syi'ah (imamah). Hanya saja demokratis yang dikehendaki Ibn Taimiyah adalah demokratis konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai syari'at[28]. Model seperti ini, menurut Ibn Taimiyah, bisa merealisasikan nilai-nilai keadilan. Bukankah Allah mengirimkan utusan-utusan-Nya supaya kita bersikap adil baik berhubungan dengan hak-hak Allah maupun dengan hak-hak manusia sebagaimana firman-Nya:
…Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya rela mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan Rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak melihatnya.[29]
2. Negara Nubuwwah dan Khilafah Nubuwwah
Tesis pokok Ibn Taimiyah mengenai negara kenabian adalah bahwa Nabi Muhammad saw. hanyalah seorang Nabi, bahwa segala aktifitasnya tercakup ke dalam fungsi kenabiannya, dan bahwa institusi imamah tidak berada di luar fungsi tersebut dan tidak pula merupakan rukun iman.[30] Pada masa Nabi masih hidup imamah tidak diperlukan, konsep imamah muncul setelah wafatnya Nabi. Ibn Taimiyah memiliki alasan-alasan yang kuat untuk membedakan rejim nubuwwah dengan negara Islam yang lahir setelah Muhammad meninggal dunia. Seorang raja, menurutnya, kepatuhan rakyat kepadanya karena ia adalah seorang raja. Tetapi, kita tentu menyadari bahwa Muhammad harus dipatuhi bukan karena dia seorang kepala negara tetapi karena dia adalah Rasul Allah.[31]
Sebenarnya inti tesis Ibn Taimiyah di atas dikarenakan pertama, penyangkalannya terhadap teori ilahiah mengenai imamah yang dikemukakan kaum Syi'ah, sedang ia tidak menyangkal fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad adalah seorang imam yang sejati. Kedua, menurutnya, kaum Muslimin tidak pernah mementingkan sesuatupun juga melebihi iman. Ketiga, bahwa detail-detail penataan negara tidak perlu disebutkan di dalam al-Qur'an. Negara, menurutnya, harus dinamis dan progresif di dalam sifat dan kondisinya.[32]
Berkaitan dengan khilafah Nubuwwah, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa perkataan khilafah, seperti terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah, tidak mengandung signifikansi religius dan politik.[33] Mengenai empat sahabat (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali), Ibn Taimiyah lebih suka menyebtunya sebagai khalifah an-Nubuwwah.[34]
Menurut penulis persoalan apakah perkataan khilafah di dalam al-Qur'an maupun hadits mengandung signifikansi religius dan politik atau tidak memang masih menjadi perdebatan, bahkan kalau Ibn Taimiyah telah secara tegas menyatakan tidak. Tetapi bahwa khilafah itu pernah ada dalam sejarah perpolitikan Islam terlepas dari sebutan yang digunakan sebagai penggantinya juga merupakan sesuatu yang tidak bisa terbantahkan dan hal ini juga diakui oleh Ibn Taimiyah. Menurutnya khilafah pernah ada di dalam sejarah sebagai sebuah institusi politik.
D. Implikasi Pemikiran Politik Ibn Taimiyah Terhadap Pemikiran Politik Islam Modern
Ibn Taimiyah yang bermadzhab Hambali dalam banyak—meskipun tidak semua—perkara hukum dan teologis, dan seorang penganut Salafiyah pada bidang yang lebih luas, sangat berpengaruh kuat di kalangan Sunni konservatif dan, dalam periode modern, di kalangan kaum liberal dan konservatif. Sejumlah gagasan Ibn Taimiyah relevan dengan masyarakat dan politik karena menurutnya agama dan negara berkaitan erat (al-Islam al-din wa al-daulah). Gagasan-gagasannya tersebut ada yang bermakna positif tapi banyak juga yang berimplikasi negatif. Di antara gagasannya yang berimplikasi negatif misalnya, dia mendefinisikan orang Mongol sebagai kafir walaupun mereka memiliki wacana Islam publik. Dia memiliki antipati umum kepada ahl al-kitab.[35]
Pemikiran takfir semacam ini, di zaman modern, banyak diikuti oleh gerakan-gerakan militan-radikal seperti tampak pada pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna dan sayyid Qutb dengan konsepnya yang terkenal "jahiliyah modern". Pemikiran Ibn Taimiyah juga menjadi inspirasi bagi Muhammad Abd al-Salam Faraj, juru bicara intelektual dari kelompok yang merekayasa pembunuhan atas Anwar Sadat. Dalam sebuah risalahnya yang berjudul al-Risalah al-Faridhah, ia mengutip fatwa Ibn Taimiyah tentang orang Mongol sebagai preseden dalam takfirnya terhadap penguasa dan otoritas religius kontemporer.[36]
Implikasi positif dari pemikiran politik Ibn Taimiyah misalnya dalam hal pemahamannya yang tidak kaku terhadap konsep khilafah. Menurutnya, model negara boleh apa saja asalkan bisa merealisasikan tujuan-tujuan sebuah negara, yaitu kemaslahatan umat manusia, menciptakan keadilan dan menegakkan syari'at Allah. Berkaitan dengan konsep kepala negara (khalifah), Ibn Taimiyah memberi peluang bagi adanya pluralisme dalam dunia Islam. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa umat Islam tidak harus mempunyai hanya seorang khalifah, tetapi dibolehkan adanya beberapa khalifah dan beberapa negara yang menjadi daerah kekuasaan masing-masing khalifah itu.[37] Pandangan yang cukup realistis mengingat pada masa Ibn Taimiyah secara de facto tidak hanya terdiri dari satu kekhalifahan, tetapi terdiri dari lebih satu kekhalifahan dan beberapa kerajaan atau dinasti.
Menurut penulis banyak orang yang menjadikan pendapat atau pemikiran Ibn Taimiyah sebagai sandaran dalam tindakannya yang negatif karena ketidakmengertian atau paling tidak telah terjadi kesalahan dalam memahami pemikiran Ibn Taimiyah walaupun dalam kasus-kasus tertentu penulis juga sependapat bahwa ada pemikiran Ibn Taimiyah yang berpotensi menimbulkan hal-hal baik pandangan maupun sikap yang negatif dan merugikan.
E. Penutup
Pemikiran politik seseorang memang akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosio-religius di mana seseorang tinggal dan berinteraksi, termasuk pemikiran politik Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah yang hidup pada masa dunia Islam sedang mengalami puncak disintegrasi poltiik, dislokasi sosial dan dekadensi akhlak serta moral jelas sangat berpengaruh terhadap model pemikiran-pemikiran politiknya. Jika demikian halnya, maka konsep takfirnya terhadap orang-orang Mongol, meskipun sudah masuk Islam, bisa dipahami. Apalagi dia dan keluarganya harus mengungsi ke Damaskus karena serangan tentara Tartar yang sangat bengis dan kejam.
Pemikiran politik Ibn Taimiyah begitu amat penting di dalam sejarah politik Islam, bahkan hingga saat ini. Tesisnya yang mengatakan bahwa rejim yang ditegakkan Nabi adalah rejim nubuwwah dan bukan imamah, sedang imamah baru ada setelah Nabi wafat, perlu senantiasa dikaji. Wallahu 'A'lam.
DAFTAR PUSTAKA
Amin, Muhammad, Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fikih Islam, Jakarta: INIS, 1991.
Esposito, John L., Ensiklopedi Oxford-Dunia Islam Modern, penerj. Eva Y.N., Femmy Syahrani, Jarot W., Poerwanto, Rofik S., cet. 1. Bandung: Mizan, 2001.
Hamadah, Abdul Ghani, Fadh al-Dzakirin wa al-Raddu 'Ala al-Munkirin. Suria: t.p., 1971.
Katsir, Ibn, al-Bidayah wa an-Nihayah, jilid IX juz 14. Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, t.th.
Khan, Qomaruddin, The Political Thought of Ibn Taimiyah, 2nd edition. Pakistan: Islamic Research Institute, 1985.
Madjid, Nurcholish, Khazanah Intelektual Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
Rojak, Jeje Abdul, Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah, cet. 1. Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara Ajaran , Sejarah dan Pemikiran, edisi 5. Jakarta: UI Press, 1993.
Taimiyah, Ibn, al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyyah, cet. 2. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1951.
---------, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah, jilid 1. Kairo: Maktabah Dar al-'Urubat, 1962.
---------, Majmu' Rasail, al-Hisbah. Kairo: t.tp., 1323.
[1] Hal ini tidak terlepas dari proyek besar Ibn Taimiyah yang ingin memberantas praktik-praktik bid'ah, khurafat, tahayul dan mistik yang menurutnya menjadi pangkal penyebab kemunduran dan kejatuhan Islam dan umat Islam.
[2] Ibn Katsir, al-Bidayah wa an-Nihayah, jilid IX juz 14, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, t.th), halm. 135-136. Lihat juga Muhammad Amin, Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fikih Islam, (Jakarta: INIS, 1991), halm. 7.
[3] Amin, Ijtihad, halm. 7-8.
[4] Ibid., halm. 9-10.
[5] Qomaruddin Khan, The Political Thought of Ibn Taimiyah, 2nd edition, (Pakistan: Islamic Research Institute, 1985), halm. 2.
[6] Amin., Ijtihad, halm. 12.
[7] Khan, The Political, halm. 5-6.
[8] Ibid., halm. 7. Konflik selanjutnya misalnya dengan kaum sufi yang disponsori Ibn 'Ata' as-Sukandari. Untuk mengetahui komentar-komentar penentangnya, penulis kutipkan pernyataan al-ustadz Abdul Ghani Hamadah. Ia menyatakaan bahwa orang-orang ahli bid'ah mengagungkan dirinya sendiri. Mereka berkata kami adalah peniolong sunnah, kami salafiyun, kami mujaddidun sebagaimana yang dikatakan oleh guru mereka, Ibn Taimiyah. Padahal sebenarnya merekalah ahli bid'ah dari golongan yang sesat karena 1) penyimpangan mereka dari imam mazhab yang empat dan dari jumhur ulama kaum Muslimin, 2) paham antrophomorpisme/tajsim mereka terhadap sifat-sifat Allah, dan 3) mengkafirkan ulama-ulama dan auliya terkemuka. Hamadah juga mengutip komentar-komentar ulama mengenai diri Ibn Taimiyah, mislanya 'Alauddin al-Bukhari mengatakan bahwa Ibn Taimiyah kafir, Zainuddin al-Hambali menyebutnya kafir, imam as-Subki mengkafirkan Ibn Taimiyah karena ia telah mengkafirkan umat Islam dan menyerupakan mereka dengan kaum Yahudi dan Nasrani di dalam tafsirnya, Ibn Hajar menyebut Ibn Taimiyah sebagai hamba yang ditelantarkan, disesatkan, dibutakan, dibisukan, dan dihinakan Allah dan komentar-komentar ulama lainnya. Periksa al-Ustadz Abdul Ghani Hamadah, Fadh al-Dzakirin wa al-Raddu 'Ala al-Munkirin (Suria: t.p., 1971), halm. 22-23.
[9] Amin, Ijtihad, halm. 13.
[10] Khan, The Political,halm. 5.
[11] Jeje Abdul Rojak, Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah, cet. 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), halm. 126.
[12] Khan, "Pendahuluan", halm. ii.
[13] Ibn Taimiyah, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah, jilid 1 (Kairo: Maktabah Dar al-'Urubat, 1962), halm. 26.
[14] Khan, The Political,halm. 24.
[15] Ibid., halm. 25.
[16] Ibid., halm. 28.
[17] Ibn Taimiyah, al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyyah, cet. 2 (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1951), halm. 172-173.
[18] Ibid., halm. 173.
[19] Disebutkan bahwa Allah menolong pemerintahan yang adil walaupun yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan tidak menolong pemerintahan yang sewenang-wenang walaupun yang dimiliki oleh orang-orang Muslim. Lihat Ibn Taimiyah, Majmu' Rasail, al-Hisbah (Kairo: t.tp., 1323), halm. 36. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa sehari bersama seorang pemimpin yang adil itu lebih utama daripada beribadah enam puluh tahun. Lihat juga Ibn Taimiyah, al-Siyasah, halm. 22.
[20] Ibid., halm. 20.
[21] Konsep ahl al-Syawkah yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah berbeda dengan konsep yang pernah diajukan oleh al-Ghazali. Menurut al-Ghazali ahl al-Syawkah adalah para penguasa yang sedang berkuasa pada masanya. Dalam konteks al-Ghazali yang dimaksud adalah para penguasa Turki dari Dinasti Saljuq yang menjadi penguasa di kota Baghdad.
[22] Khan, The Political,halm. 234.
[23] Khan, The Political halm. 235.
[24] Ibn Taimiyah, As-Siyasah, halm. 13-21.
[25] Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran , Sejarah dan Pemikiran, edisi 5. (Jakarta: UI Press, 1993), halm. 85-86.
[26] Pendapat Ibn Taimiyah ini bertentangan dengan pendapatnya sendiri yang tertuang dalam bukunya, Minhaj. Ia menerangkan syarat-syarat di dalam pemilihan seorang imam, yaitu: 1) harus dari suku Quraisy, 2) harus diangkat melalui konsultasi di antara orang-orang Muslim, 3) harus mendapatkan sumpah setia dari orang-orang Muslim, dan 4) harus bersifat adil. Periksa Ibn Taimiyah, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Naqd Kalam al-Syi'ah wa al-Qadariyah, jilid 2. (Kairo: Maktabah Dar al-'Urubat, 1962), halm. 86-89.
[27] Rojak, Politik, halm. 166-167.
[28] Ibid., halm. 179. Tampaknya pemikiran Ibn Taimiyah ini di kemudian hari menjadi inspirasi bagi Sayyid Abu A'la Maududi untuk menyusun teori politiknya. Menurut Maududi sistem politik Islam bukan teokrasi dan bukan pula demokrasi sebagaimana di Barat. Menurutnya sistem politik Islam lebih merupakan perpaduan antara keduanya sehingga bisa disebut dengan teo-demokrasi. Lebih lengkapnya lihat Maududi, Political Theory of Islam, (Lahore: Islamic Publications Limited, 1960).
[29] Al-Qur'an, 57:25.
[30] Khan, The Political,halm. 54.
[31] Ibid., halm. 57-58.
[32] Ibid., halm. 56.
[33] Ibid., halm. 137.
[34] Ibid., halm. 146.
[35] John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford-Dunia Islam Modern, penerj. Eva Y.N., Femmy Syahrani, Jarot W., Poerwanto, Rofik S., cet. 1 (Bandung: Mizan, 2001), halm. 244.
[36] Ibid., halm. 245.
[37] Nurcholish Madjid, Khazanah Intelektual Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), halm. 42.
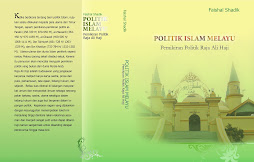



Tidak ada komentar:
Posting Komentar